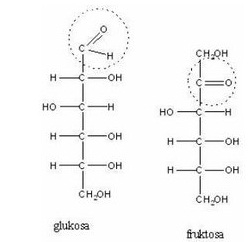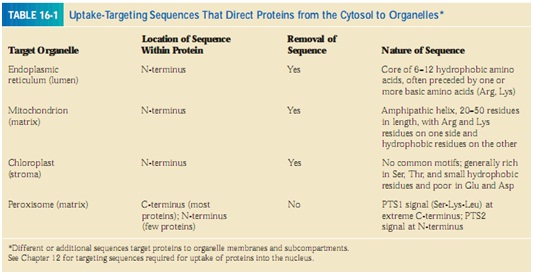Showing posts with label biokim. Show all posts
Showing posts with label biokim. Show all posts
Sunday, September 8, 2013
Monday, November 26, 2012
Anabolisme
Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks, seperti
karbohidrat, protein dan lemak, dari molekul-molekul yang sederhana.
Pembentukan karbohidrat yang dibahas pada materi kali ini adalah pembentukan
karbohidrat pada tumbuhan, yang merupakan makhluk hidup autotrof yaitu makhluk
hidup yang dapat memanfaatkan sumber karbon anorganik. Pembentukan karbohidrat
pada tumbuhan yaitu melalui proses fotosintesis.
Fotosintesis
Organisme fotosintetik dan heterotrofik hidup didalam
keadaan seimbang pada biosfer kita. Tanaman fotosintetik menangkap energy surya
dalam bentuk ATP dan NADPH yang dipergunakan sebagai sumber energi untuk
membuat karbohidrat dan komponen sel organik lainnya dari karbondioksida dan
air. Bersamaan dengan itu organisme tersebut membebaskan oksigen ke atmosfer.
Sebaliknya heterotrof aerobik mempergunakan oksigen yang dibentuk untuk
menguraikan produk organik berenergi tinggi dari fotosintesis menjadi CO2
dan H2O untuk membentuk kembali ATP guna keperluan aktifitas sel itu
sendiri. Karbondioksida yang dibentuk oleh respirasi pada heterotrof kembali ke
atmosfer, untuk dipergunakan kembali oleh organisme fotosintetik. Oleh karena
itu, energi surya memberikan tenaga pendorong bagi daur karbondioksida dan
oksigen atmosfer secara berkesinambungan melalui biosfer kita.
6CO2 +
12H2O + Energi cahaya→C6H12O6+6O2+6H2O
Proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan tinggi dibagi
dalam dua tahap, yaitu tahap reaksi terang yang terjadi jika tumbuhan diberi cahaya dan tahap reaksi gelap yang terjadi dengan atau tanpa adanya cahaya matahari. Di dalam sel
fotosintetik eukariotik, reaksi gelap dan reaksi terang terjadi di dalam
kloroplas.
Bentuk kloroplas
berbeda pada setiap spesies.organel ini dikelilingi oleh membran luar yang
bersambungan, dan bersifat rapuh.suatu sistem membran membungkus ruangan bagian
dalam organel, di dalamnya ,terdapat banyak kantung pipih yang dikelilingi
membran, yang dinamakan tilakoid, yang biasanya tersusun berlapis-lapis,
dinamakan grana. Membran tilakoid mengandung semua pigmen fotosintetik pada
kloroplas dan semua enzim yang diperlukan bagi reaksi primer yang bergantung
pada cahaya matahar. Cairan di dalam ruang yang melingkupi kantung tilakoid
atau stroma mengandung hampir semua enzim yang diperlukan bagi reaksi gelap,
yang mereduksi CO2 membentuk glukosa. Berikut ini penjelasan lebih lanjut
mengenai tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap.
1.TAHAP REAKSI
TERANG
Reaksi terang terjadi jika ada cahaya, misalnya cahaya
matahari. Energi dtangkap olaeh klorofil dan digunakan untuk memecah molekul
air, dan pemecahan ini disebut fotolisis.Reaksi terang adalah proses untuk
menghasilkan ATP dan reduksi NADPH. Reaksi ini diawali dengan penangkapan foton
oleh pigmen sebagai antena. Fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi
pada gelombang chaya panjang tertentu. Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang
berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem yaitu fotosistem II dan
fotosistem I.
Fotosistem
I dan Fotosistem II
Reaksi
terang cahaya dalam proses fotosintesis penyerapan energy matahari oleh
klorofil dimana dilepaskan O2, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut
fotosistem I yang menyangkut penyerapan energy matahari pada panjang gelombang
di sekitar 700nm dan tidak melibatkan proses pelepasan O2. Bagian kedua yang
menyangkut penyerapan energy matahari pada panjang gelombang di sekitar 680nm,
disebut fotosistem II yang melibatkan pembentukan O2.
Friday, November 23, 2012
protein
Protein merupakan polimer asam amino. Struktur umum asam amino
Terdapat 20 macam asam amino dengan penggolangan asam amino sebagai berikut :
1. Asam amino non polar
Adalah asam amino yang tidak dapat larut dalam air.
2. Asam amino polar tidak bermuatan
Adalah asam amino yang dapat larut dalam air.
3. Asam amino polar bermuatan positif
Adalah asam amino yang dapat larut dalam air, bermuatan negatif sehingga bersifat asam.
4. Asam amino polar bermuatan negatif
Adalah asam amino yang dapat larut dalam air, bermuatan positif sehingga bersifat basa.
Contoh-contohnya :
Asam amino-asam amino berikatan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida.
Terdapat 4 macam struktur pada protein, antara lain :
1. Struktur primer
2. Struktur sekunder
Wednesday, October 17, 2012
RNA ( Ribonucleic acid )
makalah terkait transkripsi RNA
laporan yang terkait
transkripsi RNA
Sintesis protein
melibatkan DNA sebagai pembuat rantai polipeptida. Meskipun begitu, DNA tidak
dapat secara langsung menyusun rantai polipeptida karena harus melalui RNA.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa DNA merupakan bahan informasi genetik
yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi yang dikode di dalam
gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Informasi
ditransfer secara akurat dari DNA melalui RNA untuk menghasilkan polipeptida
dari urutan asam amino yang spesifik.
Selain DNA,
sebagian besar sel prokariot dan sel eukariot juga memiliki asam nukleat yang
lain yaitu RNA. RNA singkatan dari ribonucleic acid atau asam
ribonukleat. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga
RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibanding DNA. Tidak seperti DNA
yang biasanya dijumpai di dalam inti sel, kebanyakan RNA ditemukan di dalam
sitoplasma, terutama di ribosom.
Beberapa macam
virus seperti virus Mosaik Tembakau atau TMV (“Tobacco Mosaic Virus”) dan Virus
Influenza tidak memiliki DNA, melainkan hanya RNA saja. Jadi, seluruh bahan
genetik di dalam selnya berupa RNA saja, sehingga membawa segala
pertanggungjawaban seperti yang dibawa DNA. Oleh karena itu RNA demikian itu
sering dinamakan juga RNA genetik, sedangkan RNA di dalam sel biasa disebut RNA
nongenetik (akan dipelajari lebih lanjut pada materi Macam RNA). Berikut akan
diuraikan tentang struktur RNA dan macam RNA.
RNA dapat dibedakan
menjadi dua kelompok utama, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik.
RNA genetik memiliki
fungsi yang sama dengan DNA, yaitu sebagai pembawa keterangan genetik. RNA
genetik hanya ditemukan pada makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA,
misalnya virus. Dalam hal ini fungsi RNA menjadi sama dengan DNA, baik sebagai
materi genetik maupun dalam mengatur aktivitas sel.
RNA non-genetik
tidak berperan sebagai pembawa keterangan genetik sehingga RNA jenis ini hanya
dimiliki oleh makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Berdasarkan letak dan
fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi mRNA, tRNA, dan rRNA.
- mRNA (messenger RNA) atau ARNd (ARN duta)
mRNA merupakan RNA
yang urutan basanya komplementer (berpasangan) dengan salah satu urutan basa
rantai DNA. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal
linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Panjang pendeknya mRNA
berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang akan disusun.
Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan
kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak
sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Adapun fungsi utama mRNA adalah
membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma.
mRNA ini dibentuk bila diperlukan dan jika tugasnya selesai, maka akan
dihancurkan dalam plasma.
- tRNA (transfer RNA) atau ARNt (ARN transfer)
RNA jenis ini
dibentuk di dalam nukleus, tetapi menempatkan diri di dalam sitoplasma. tRNA
merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA.
Fungsi lain tRNA adalah mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan
disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Bagian tRNA yang
berhubungan dengan kodon dinamakan antikodon.
- rRNA (ribosomal RNA) atau ARNr (ARN ribosomal)
RNA ini disebut
ribosomal RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. rRNA
bersama protein membentuk ribosom, ialah benda-benda berbentuk butir-butir
halus di dalam sitoplasma. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA
ribosom adalah sebagai mesin perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke
satu arah sepanjang mRNA. Di dalam ribosom, molekul rRNA ini mencapai 30-46%.
transkripsi RNA
Tuesday, October 16, 2012
karbohidrat
Secara umum definisi
karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom Karbon (C) dan air (H2O) sehingga mempunyai rumus empirik (CH2O)n.
Secara kimia, karbohidrat didefinisikan sebagai
polihidroksi aldehida (aldosa) ataupun
polihidroksi keton (ketosa).
aldosa ketosa
Disebut suatu aldosa karena pada strukturnya
terdapat gugus karbonil yang letaknya di ujung. Dan disebut suatu ketosa karena pada strukturnya
terdapat gugus karbonil yang letaknya di tengah.
Penggolongan Karbohidrat
Berdasarkan
jumlah gugus gulanya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida,
dan polisakarida.
a. A. Monosakarida
Monosakarida merupakan karbohidrat dengan satu gugus
gula.
Contoh:
B. Disakarida
Disakarida merupakan karbohidrat dengan 2 gugus gula.
Penggabungan 2 gugus gula ini melalui reaksi dehidrasi. Contoh disakarida
adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa.
Pembelahan Sel
artikel yang terkait struktur dan fungsi nukleus, transkripsi RNA protein, siklus sel, pembelahan sel
Mitosis.
Merupakan proses pembelahan yang menghasilkan dua sel
anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel
induknya. Mitosis terjadi pada perbanyakan sel somatis. Kromosomya berpasangan
sehingga disebut diploid (2n). Tahap-tahap pembelahan mitosis adalah sebagai
berikut :
Profase.
Pada fase ini, sel induk yang akan membelah
memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap
di tempat dan yang satu bergerak ke kutub yang berlawanan. Tiap sentriol
memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut benang spindel. Membran
inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Lalu,
butiran kromatin memnajang menjadi benang kromatin yang kemudian memendek dan
menebal menjadi kromosom dengan bagian yang menggenting disebut sentromer. Tiap
sentromer mengandung kinetokor. Kemudian, kromosom berduplikasi menjadi dua
bagian yang disebut kromatid. Bersamaan dengan itu, anak inti mengecil dan
tidak nampak. Dengan demikian, kromatid terjerat pada benang spindel. Sementara
itu, benang spindel meluas ke segala arah disebut aster. Di akhir profase,
selubung benang inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindel
di kinetokor. Kromosom duplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajar di
ekuator.
Metafase.
Periode selama kromosom berada di ekuator disebut
metafase. Membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di bidang ekuator.pada
fase ini kromosom tampak paling jelas.
Anafase.
Kromatid bergerak menuju arah kutub-kutub yang
berlawanan, kinetokor yang masih melekat pada benang spindel berfungsi
menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang.
Telofase.
Kromatid-kromatid mengumpul pada kutub. Benang spindel
menghilang, kromatid menjadi kusut dan terdapat butiran kromatid. Selaput inti
terbentuk kembali dan nukleolus terlihat kembali. Pada bagian ekuator terjadi
lekukan yang makin lama makin ke dalam sehingga membagi sel induk menjadi dua
bagian yang merupakan sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang
sama dengan sel induk.
Interfase.
Fase ini merupakan fase persiapan sel untuk melakukan
pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi.
Siklus Sel
Sel sebagai unit terkecil kehidupan
tentunya mengalami pertumbuhan sel. Pada sel yang sedang tumbuh selalu
mengalami siklus sel, yang merupakan serangkaian proses yang berlangsung sejak
sel itu terbebtuk hingga siap mulai membelah. Siklus sel sendiri meliputi
pertambahan massa dan duplikasi bahan genetic yang dikenal sebagai interfase
dan pembelahan sel. Pada sel eukariotik pembelahan sel ada dua macam, yaitu
mitosis dan meiosis.
Para ahli biologi lebih banyak
mencurahkan perhatiannya pada fase pembelahan sel karena perubahan- perubahan
yang dramatis yang berlangsung dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Oleh
karena itu, interfase juga meerupakan ‘fase istirahat’. Pada interfase terjadi
beberapa kegiatan yang intensif, antara lain biosintesis adan deoksiribonukleat
(ADN) dan pembagian komponen-komponen kromosom menjadi dua bagian yang sama.
Sehingga ukuran sel bertambah kurang lebih dua kali lipat.
Pada interfase berlangsung serangkaian proses yang
komplek sebagai persiapan untuk membagikan materi-materi yang terdapat pada
sebuah sel kepada sel anak dengan jumlah yang sama. Sebelum membelah,
komponen-komponen molekuler sel yang penting dalam sel telah digandakan menjadi
dua kali lipat, sehingga sebenarnya pembelahan sel merupakan fase terakhir dari
perubahan-perubahan tingkat molekul yang sedang berlangsung. Berikut merupakan
gambar ringkasan peristiwa-peristiwa besar dalam
siklus sel eukariotik dan kondisi kromosom induk.
Dalam sel
berkembang biak, G1 adalah periode antara kelahiran sel mitosis dan inisiasi
sintesis DNA, yang menandai awal fase S. Pada akhir fase S, kromosom yang
direplikasi terdiri dari dua DNA dan terkait kromosom. Akhir G2 ditandai oleh
terjadinya mitosis, memisahnya gelendong mitosis (garis merah) dan menuju
ke kutub masing-masing, diikuti pembagian sitoplasma (sitokinesis) untuk
menghasilkan dua sel anak. G1, S, dan fase G2
secara kolektif disebut sebagai interfase, periode antara satu mitosis
dan berikutnya.
Berdasarkan penelitian-penelitian
sitokimia (antara lain dengan menggunakan zat warna Feolgen) dan penelusuran
dengan timidin radioaktif, Howard sdan Pele membagi siklus sel menjadi empat
periode yang berurutan, yaitu periode G1 (G = gap), periode S
(sintesis), periode G2, dan mitosis. Sintesis ADN hanya berlangsung
pada periode S. selam periode G2 pada suatu sel mengandung ADN
sebanyak dua kali lipat jika dibanding pada periode G1. Sel-sel anak
yang baru dibentuk pada mitosis kembali mengandung jumlah ADN seperti pada
periode G1.
Dalam membahas
mitosis, kita biasanya menggunakan istilah kromosom yang merupakan bagian yang
sangat berperan dalam pewarisan sifat. Kromosom ini jelas terlihat saat
proses pembelahan sel jika dilihat dengan mikroskop cahaya. Selama
interfase, bagian dari siklus sel antara akhir satu M fase dan awal berikutnya,
membentuk sambungan dengan retikulum endoplasma . Dengan terjadinya mitosis
dalam profase, benang spindle ditarik ke dalam retikulum retikulum, dan Membran
Golgi terurai menjadi vesikula. mikrotubulus membongkar dan berkumpul
kembali ke aparat mitosis yang terdiri dari berbentuk bola bundel dari
mikrotubulus (gelendong) dengan cluster berbentuk bintang dari mikrotubulus
memancar dari setiap ujung, atau gelendong tiang. Selama periode metafase
mitosis, sebuah multiprotein kompleks, yang kinetokor, berkumpul di
masing-masing sentromer. Itu kinetochore dari kromatid saudari kemudian bergaul
dengan mikrotubulus datang dari gelendong yang berlawanan kutub.
Selama periode anafase mitosis,
kromatid terpisah. Mereka awalnya ditarik oleh protein motor sepanjang
mikrotubulus gelendong menuju kutub yang berlawanan dan kemudian yang lebih
jauh terpisah sebagai gelendong mitosis berelongasi. Setelah selesai Pemisahan
kromosom, gelendong mitosis disassembles dan kromosom decondensasi selama
telofase. Membran inti kembali terbentuk di sekeliling terpisah kromosom saat
mereka decondensasi . Pembagian sitoplasma
secara fisik, disebut sitokinesis kemudian
menghasilkan dua sel anak sebagai kompleks Golgi bentuk ulang di
masing-masing sel anak. Setelah mitosis sel bersiklus memasuki fase G1,
memulai pergantian siklus lain. Pada vertebrata dan diploid ragi, sel-sel di G1
memiliki jumlah kromosom diploid (2n).
Transkripsi RNA Protein
Transkripsi mempunyai ciri-ciri kimiawi yang serupa
dengan sintesis/replikasi DNA, yaitu :
1. Adanya
sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Bedanya dengan sumber
basa untuk sintesis DNA hanyalah pada molekul gula pentosanya yang tidak berupa
deoksiribosa tetapi ribosadan tidak adanya basa timin tetapi digantikan oleh urasil.
Jadi, keempat nukleosida trifosfat yang diperlukan adalah adenosin trifosfat
(ATP), guanosin trifosfat (GTP), sitidin trifosfat (CTP), dan uridin trifosfat
(UTP).
2. Adanya untai
molekul DNA sebagai cetakan. Dalam hal ini hanya salah satu di antara kedua
untai DNA yang akan berfungsi sebagai cetakan bagi sintesis molekul RNA. Untai
DNA ini mempunyai urutan basa yang komplementer dengan urutan basa RNA. hasil
transkripsinya, dan disebut sebagai pita antisens. Sementara itu, untai DNA
pasangannya, yang mempunyai urutan basa sama dengan urutan basa RNA, disebut
sebagai pita sens.
3. Sintesis
berlangsung dengan arah 5’→ 3’ seperti halnya arah sintesis DNA. Gugus 3’- OH
pada suatu nukleotida bereaksi dengan gugus 5’- trifosfat pada nukleotida
berikutnya menghasilkan ikatan fosofodiester dengan membebaskan dua atom
pirofosfat anorganik (PPi). Reaksi ini jelas sama dengan reaksi polimerisasi
DNA. Hanya saja enzim yang bekerja bukannya DNA polimerase, melainkan RNA
polimerase. Perbedaan yang sangat nyata di antara kedua enzim ini terletak
pada kemampuan enzim RNA polimerase untuk melakukan inisiasi sintesis RNA tanpa
adanya molekul primer.
Tahap-tahap transkripsi adalah
sebagai berikut :
Struktur Nukleus
Inti sel terdiri dari beberapa
bagian, yaitu membran inti/ nuclear envelope (Karioteka), nukleoplasma
(kariolimfa), kromatin dan nukleolus (anak inti).
bagian-bagian dalam nukleus :
1. Membran Inti
Membrane inti atau selubung inti merupakan struktur
pembatas materi initi sel dengan sitoplasma. Struktur membran inti saat diamati
di bawah mikroskop electron tampak sebagai dua lapisan membran yang
masing-masing dipisahkan oleh celah sebesar 20-30 nm. Membran inti luar
berhubungan dengan reticulum endoplasma, karena itu ruang antara membran inti
dalam dan luar adalah langsung berhubungan dengan lumen reticulum endoplasma.
Fungsi yang penting dari membran inti adalah bekerja sebagai pembatas yang
memisahkan kandungan inti sel dengan sitoplasma. Seperti membran sel yang lain,
setiap membran inti tersusun dari dua lapis phospolipid (untuk selanjutnya
digunakan istilah “phospolipid bilayer”) yang hanya permeable terhadap
molekul kecil non polar. Struktur membran inti juga dilengkapi dengan
lubang-lubang yang disebut porus nuclearis, yaitu lubang pada selubung inti
yang menghubungkan nucleolus dengan sitoplasma. Sel melalui lubang-lubang ini
dapat mentransfer substansi sel yang berada di dalam nukleus ke luar nucleus (sitoplasma).
Subsatansi sel yang ditransfer ke luar sel adalah molekul RNA yang berkaitan
erat dengan sintesis protein di sitoplasma.
Friday, May 25, 2012
Mekanisme Sorting Protein dari Sitosol ke Organel
Sorting
ini berarti penyeleksian. Protein di sintesis di dalam sitosol kemudian
beberapa di masukkan ke dalam mitokondria, kloroplas, dan peroksisom melalui
tahap seleksi. Mitokondria dan kloroplas masing-masing mempunyai membran
bilayer ganda, sedangkan peroksisom memiliki membran bilayer tunggal. Perbedaan
dari ketiga sorting dapat dilihat
pada table berikut ini.
A. Sorting Protein ke Mitokondria
Ada 4 bagian dalam
mitokondria yang berperan dalam pengiriman protein, yaitu bagian membran luar
mitokondria, membran dalam mitokondria, ruang intermembran, dan matriks
mitokondria. Meskipun mitondria mempunyai DNA dan ribosom sendiri tapi sebagain
besar proteinnya disintesis di sitosol yang dikode oleh gen nukleus. Protein
yang ditujukan untuk mitokondria mempunyai sinyal khusus yang dapat dikenali
oleh mitokondria. Protein yang akan masuk ke matrik mitokondria mengandung untaian
sinyal yang dapat dikenali mitokondria dan berada pada N-terminus.
1. Prekusor protein pada
ribosom sitosol mengandung chaperon
2. Setelah protein dengan
reseptor import pada membran bertemu, kemudian protein ini akan dibawa oleh
reseptor import ke pori protein intergral pada membran luar ynag langung
berhubungan dengan protein intregral pada membran dalam
3. Untaian pengarah
dikeluarkan dengan bnatuan enzim matrik pretease
struktur dan fungsi peroksisom
Peroksisom
Organel ini ditemukan pada
sel hewan, sel tumbuhan tertentu maupun sel ragi. Peroksisom pertama kali
ditemukan oleh De Duve dan kawan-kawannya pada tahun 1965 di dalam sel-sel
hati. Di dalam peroksisom ditemukan beberapa macam enzim oksidase dan enzim katalase.
Oleh karena enzim - enzim ini berperan dalam pembentukan katalase yaitu dalam
pembentukan dan pembongkaran hidrogen peroksida (H2O2) ,
maka organel tersebut dinamakan peroksisom. Pada sel tumbuhan, fungsi organel
ini berkaitan dengan siklus glioksilat sehingga dinamakan glioksisom. Pada
tumbuhan, peroksisom akan menguraikan asam glikolat yang dihasilkan dari proses
fotosintesis kemudian mendaur ulang kembali molekul untuk dikembalikan ke
kloroplas.
Di dalam sel, peroksisom
berbentuk bulat telur dengan diameter kurang lebih antara 0,5 - 0,7 mikrometer,
hanya dibungkus oleh selapis membran. Jumlah peroksisom untuk tiap sel
bervariasi antara 70-700. Peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri
sehingga dapat membentuk peroksisom anak. Protein dan lipid yang diperlukan
ditransfer dari sitosol. Selain berfungsi untuk pembentukan dan perombakan H2O,
menjadi substrat organik dan H2O, peroksisom juga berfungsi untuk
merombak asam lemak yang tersimpan dalam biji menjadi glukosa untuk proses
perkecambahan. Peroksisom memiliki 1 membran dan tidak memiliki DNA atau
ribosom. Karena peroksisom tidak memiliki genom, bagaimanapun juga
semua protein harus diimport. Peroksisom sedemikian mirip dengan RE pada
replikasi membrannya, berikatan dengan organel yang ada tanpa genom.
Peroksisom ditemukan di semua
sel eukaryotik. Mereka terdiri dari enzim oksidatif seperti katalase dan urate
oksidase, pada berbagai konsentrasi yang tinggi di beberapa sel. Seperti
mitokondria, peroksisom merupakan tempat besar untuk penghasilan oksigen.
Satu hipotesis adalah bahwa peroksisom merupakan sisa organel tua yang
melaksanakan metabolisme oksigen pada ansestor primitif sel eukaryotik.
Peroksisom terdiri dari satu
atau lebih enzim yang menggunakan oksigen molekuler untuk mengubah atom
hidrogen pada subtrat organik yang spesifik pada reaksi oksidasi yang
menghasilkan hidrogen peroksida sebagai hasil samping.
Reaksi :
RH2 + O2 → R + H2O2
Katalase dengan enzim lain
pada organel menggunakan H2O2 untuk mengoksidasi macam-macam subtrat lain
termasuk fenol, asam formic, formaldehid, dan alkohol dengan reaksi
perokdative. Tipe reaksi oksidasi ini secara khusus penting pada sel hati dan
ginjal, yang mana peroksisom akan menetralkan molekul toksik yang akan masuk ke
dalam aliran darah. Bila kita meminum athanol seperti alkohol maka ini akan
dioksidasi menjadi asetaldehid. Ketika terdapat kelebihan akumulasi H2O2 dalam
sel, maka katalase akan mengubahnya menjadi H2O ( 2H2O2 → 2H2O + O2).
Fungsi penting dari reaksi
oksidasi yang berlangsung di peroksisom adalah memecah molekul asam lemak. Pada
proses yang disebut beta oksidasi, ikatan alkil asam lemak dipendekkan menjadi
2 atom karbon yang kemudian akan diubah menjadi asetil Ko-A dan diekspor dari
peroksisom menuju sitosol untuk digunakan kembali pada reaksi biosintesis. Beta
oksidasi dalam sel mamalia terjadi pada mitokondria dan peroksisom. Peroksisom
merupakan organel yang tidak biasa dan pada sel yang berbeda dari satu
organisme dapat terdiri dari enzim-enzim yang berbeda. Mereka dapat beradaptasi
terhadap perubahan kondisi. Sel jamur yang berkembang pada gula memiliki
peroksisom yang kecil. Tetapi ketika jamur berkembang pada methanol, mereka
memiliki peroksisom yang besar yang mengoksidasi methanol, dan ketika jamur
berkembang pada asam lemak maka mereka memiliki peroksisom yang besar untuk
memecah asam lemak menjadi asetil Ko-A. Peroksisom juga memiliki peran yang
penting pada tanaman. Peroksisom yang berada di daun dimana ini mengkatalisis
oksidasi produk samping dari reaksi yang krusial yang menambahkan CO2 di
karbohidrat. Proses ini disebut dengan fotorespirasi karena ini mengikat
oksigen dan membebaskan karbondioksida. Tipe lain dari peroksisom yaitu yang
berada di bibit perkecambahan, dimana ini memainkan peran penting untuk
mengubah asam lemak pada lipid menjadi gula yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
tanaman muda. Karena pengubahan ini melalui siklus glikolat, maka peroksisom
ini juga disebut dengan glioksisom. Pada siklus glikolat 2 molekul asetil Ko-A
yang diproduksi oleh asam lemak dipecah di dalam peroksisom yang akhirnya
digunakan untuk membuat asam suksinat. Selanjutnya, ini akan meninggalkan
peroksisom dan diubah menjadi gula. Siklus glikolat ini tidak terjadi pada sel
hewan dan hewan tidak dapat mengubah asam lemak menjadi karbohidrat.
DAFTAR PUSTAKA
Djohar.
1985. Biologi Sel I (Diktat Kuliah). Yogyakarta : FMIPA UNY.
Karp,
Gerald. 2004. Cell
and Moleculer Biology. USA : Von Hoffmann press.
Murray, RK, Dk Granner, PA Mayes, VM Rodwell. 2003. Harper’s Illustrated Biochemistry.
26th edition. Amerika utara : The
McGraw-Hill Company .
Nelson, DL dan MM Cox. 2005. Principles of Biochemistry. 4th edition. W.H. Freeman and Company.
Reksoatmojo,
Issoegianti. 1994. Biologi Sel.
Yogyakarta : DEPDIKBUD.
Stryer, Lubert. 2000. Biokimia Edisi 4. Jakarta : EGC.
Suryani,
Yoni. 2004. Bilogi
Sel dan Molekuler.
Yogyakarta : FMIPA UNY.
struktur dan fungsi lisosom
Lisosom adalah organel pencerna
pada sel hewan dan di temukan disemua sel eukariotik. Lisosom
berasal dari kata lyso = pencernaan
dan soma = tubuh. Diamater lisosom
kira-kira 25-50nm - 1μm. Lisosom memiliki keanekaragaman
morfologi. Berbentuk agak bulat dan dikelilingi oleh membran tunggal bilayer
yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Yang khas dari lisosom adalah terdiri atas sekitar 50 enzim
hidrolitik yang berbeda yang dihasilkan di dalam RE kasar. Enzim
ini disebut dengan lisozom.
Enzim-enzim ini dapat menghidrolisis semua bentuk makromolekul antara lain
polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Enzim hidrolisis tersebut
bekerja optimum pada pH asam (sekitar 4,6). Kondisi asam ini dihasilkan dari
pompa proton di membran organel. Lisosom dapat mempertahankan kondisi
asam ini dengan cara membran lisosom memompa ion hidrogen dengan menghunakan
bantuan ATP dari sitosol ke dalam lumen lisosom. Proses masuknya ion hidrogen
ini karena membran lisosom mengandung protein integral yang kandungan
glikosilatnya tinggi dan terdapat garis pelindung dari karbohidrat yang mampu
melindungi membran dari kerusakan.
Contoh
enzim lisosom
Enzim
|
Substrat
|
Phosphatase :
Acid phosphatase
Acid phosphodiesterase
|
Phosphomonoesterus
Phosphodiesters
|
Nucleases :
Acid ribonuclease
Acid deoxyribinuclease
|
RNA
DNA
|
Proteases :
Cathepsin
Collagenase
|
Protein
Collagen
|
GAG-hydrolizing enzymes :
Iduronate Sulfatase
Β-galactosidase
Heparan N-sulfatase
α-N- Acetylglucosaminidase
|
Dermatan sulfate
Keratan sulfate
Heparan sulfate
Heparan sulfate
|
Polysaccharidases dan
Oligosaccharidases:
α-glucosidase
Fucosidase
α-manosidase
Sialidase
|
Glycogen
Fucosyloligosaccharides
Mannosyloligossacharides
Sialyloligosaccharides
|
Sphingolipid hydrolyzing
enzymes :
Ceramidase
Glucocerebosidase
β-Hexosaminidase
Arylsulfatase
|
Ceramide
Glucosylceramide
GM2ganglioside
Galactosylsulfatide
|
Lipid hidrolysing enzimes :
Acid lipase
Phospholipase
|
Triacylglycerols
Phospholipids
|
Lisosom berfungsi untuk
merusak/menghancurkan materi yang masuk ke dari luar sel,
menghancurkan patogen mencerna makanan, daur ulang organel yang rusak, dan
berperan dalam perkembangan embrio pada hewan. Beberapa organisme uniseluler mencerna partikel makanan
yang kemudian dibongkar secara enzimatis di dalam lisosom, dan nutrisi hasil
pencernaan akan dilepaskan ke dalam sitosol. Pada sel fagositik mamalia,
seperti makrofag dan neutrofil, berfungsi untuk mencerna mikroorganisme
berbahaya. Pencernaan bakteri atau mikroorganisme tersebut diaktifkan pada pH
rendah dari lisosom dan kemudian dicerna secara enzimatik.
Lisosom juga mempunyai peran
dalam pergantian organel, yang mengatur perusakan serta penempatan organel sel
itu sendiri, disebut autofagi. Selama proses ini berlangsung, sebuah organel
seperti mitokondria akan diselubungi oleh membran ganda yang merupakan derivat
dari sisterna RE. membran RE kemudian bergabung degan lisosom untuk membentuk
autofagolisosom.
Ketika proses autofagolisosom
selesai, organel yang dicerna dikeluarkan sebagai residual body. Berdasarkan
tipe dari sel yang bersangkutan, isi dari residual body dikeluarkan dari
dalam sel secara eksositosis atau disimpan di dalam sitoplasma disebut lipofuscin
granulLipofuscin granule akan meningkat jumlahnya seiring penambahan umur
sel.
Wednesday, May 16, 2012
koenzim dan vitamin
Beberapa
enzim hanya terdiri dari polipeptida dan mengandung gugus kimiawi selain residu
asam amino, contohnya adalah ribonuklease pankreas. Akan tetapi, enzim lain
memerlukan tambahan kimia bagi aktivitasnya; komponen ini disebut kofaktor.
Kofaktor mungkin suatu molekul anorganik seperti ion Fe2+, Mn2+,
atau Zn2+, atau mungkin suatu molekul organik kompleks yang disebut
koenzim. Beberapa enzim membutuhkan baik koenzim maupun satu atau lebih ion
logam bagi aktivitasnya. Pada beberapa enzim, koenzim, atau ion logam hanya
terikat secara lemah atau dalam waktu sementara pada protein, tetapi, pada
enzim lain, senyawa ini terikat kuat, atau terikat secara permanen yang dalam
hal ini disebut gugus prostetik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif
mengkatalisis, bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut
holoenzim. Koenzim dan ion logam bersifat stabil sewaktu pemanasan, sedangkan
bagian protein enzim yang disebut apoenzim, terdenaturasi oleh pemanasan.
Koenzim berfungsi sebagai pembawa sementara atom spesifik atau gugus
fungsionil.
Tabel 1. Koenzim
dan Senyawa yang Dipindahkan
Koenzim
|
Senyawa yang
Dipindahkan
|
Tiamin
pirofosfat
|
Aldehida
|
Flavin adenin
dinukleotida
|
Atom hydrogen
|
Nikotinamida
adenine dinukleotida
|
Ion hidrida (H-)
|
Koenzim A
|
Gugus asil
|
Piridoksal
fosfat
|
Gugus amino
|
5’-Deoksiadenosi
obalamin (koenzim B12)
|
Atom H dan gugus
alkil
|
Biositin
|
CO2
|
Tetrahidrofolat
|
Gugus
satu-karbon lainnya
|
Vitamin
adalah prekursor esensial berbagai koenzim. Karena vitamin dibutuhkan pada diet
manusia hanya dalam jumlah milligram atau mikrogram per hari, maka vitamin
disebut mikronutrien. Vitamin diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit karena
vitamin bekerja sebagai katalisator yang memungkinkan transformasi kimia
makronutrien yang secara bersama-sama disebut metabolisme. Seperti halnya
enzim, bentuk aktif vitamin hanya terdapat pada konsentrasi yang rendah di
dalam jaringan.
A.
Pengelompokan
vitamin
Vitamin
dibedakan ke dalam dua kelas yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin
yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi tiamin
(vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), asam nikotinat,
asam pantotenat, piridoksin (vitamin B6), biotin, asam folat,
vitamin B12, dan asam askorbat (vitamin C). Hampir semua vitamin
tersebut telah diketahui fungsi koenzimnya. Vitamin yang larut dalam lemak
(senyawa berminyak dan tidak larut dalam air) yaitu vitamin A, D, E, dan K.
Fungsi biokimiawi vitamin yang larut dalam lemak tidak diketahui secara jelas.
Tabel 2. Vitamin dan Peranannya pada Fungsi Enzim
Vitamin
|
Bentuk koenzim
(bentuk aktif) |
Jenis reaksi
atau proses yang dilangsungkan
|
Larut dalam
air
|
||
Tiamin
|
Tiamin
pirofosfat
|
Dekarboksilasi
asam α-keto
|
Riboflavin
|
Flavin
mononukleotida, flavin adenin dinukleotida
|
Reaksi
oksidasi-reduksi
|
Asam nikotinat
|
Nikotinamida
adenin dinukleotida, nikotin amida adenin dinukleotida fosfat
|
Reaksi oksidasi-reduksi
|
Asam pantoetat
|
Koenzim A
|
Transfer gugus
asil
|
Piridoksin
|
Piridoksal
fosfat
|
Transfer gugus
amino
|
Biotin
|
Biositin
|
Transfer CO2
|
Asam folat
|
Asam
tetrahidrofolat
|
Transfer gugus
1-karbon
|
Vitamin B12
|
Deoksi
adenosil kobalamin
|
Pemindahan 1,2
hidrogen
|
Asam askorbat
|
Tidak
diketahui
|
Kofaktor pada
reaksi hidroksilasi
|
Larut di dalam
lemak
|
||
Vitamin A
|
Retinal
|
Siklus
pengelihatan
|
Vitamin D
|
1,25-dihidroksikolekalsiferol
|
Regulasi
metabolism CO2+
|
Vitamin E
|
Tidak
diketahui
|
Perlindungan
lipida membran
|
Vitamin K
|
Tidak
diketahui
|
Kofaktor pada
reaksi karboksilasi
|
DAFTAR PUSTAKA
Djohar.
1985. Biologi Sel I (Diktat Kuliah). Yogyakarta : FMIPA UNY.
Karp,
Gerald. 2004. Cell
and Moleculer Biology. USA : Von Hoffmann press.
Murray, RK, Dk Granner, PA Mayes, VM Rodwell. 2003. Harper’s Illustrated Biochemistry.
26th edition. Amerika utara : The
McGraw-Hill Company .
Nelson, DL dan MM Cox. 2005. Principles of Biochemistry. 4th edition. W.H. Freeman and Company.
Reksoatmojo,
Issoegianti. 1994. Biologi Sel.
Yogyakarta : DEPDIKBUD.
Stryer, Lubert. 2000. Biokimia Edisi 4. Jakarta : EGC.
Suryani,
Yoni. 2004. Bilogi
Sel dan Molekuler.
Yogyakarta : FMIPA UNY.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya
Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya dan pengimplementasian di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. a. ...
-
Lisosom adalah organel pencerna pada sel hewan dan di temukan disemua sel eukariotik . Lisosom berasal dari kata lyso = pencernaan dan so...
-
42. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) A. Latar Belakang Ilmu Pengetahuan Alam ...
-
Sorting ini berarti penyeleksian. Protein di sintesis di dalam sitosol kemudian beberapa di masukkan ke dalam mitokondria,...